Oleh: Herlianto A
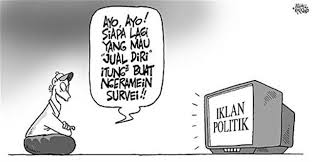 |
| Sumber: mindmata.wordpress.com There are only two things that can be lightening the world. The sun light in the sky and the press in the earth (Mark Twain) |
Apapun yang ingin disampaikan pada orang
lain harus melalui media sebagai jembatan, apakah itu bentuknya suara (speaking) atau tanda tulisan (writing) atau sandi (sign). Termasuk dakwah yang akan disampaikan
harus ada medianya (alat). Belakangan ini media dipersempit maknanya pada
pewartaan saja (pers). Baik media cetak
seperti koran, tabloid, atau majalah, maupun media visual yaitu televisi. Dua genre media itu menyampaikan warta
kepada publik. Banyak hal yang disampaikan
mulai yang sifatnya entertainment, politik, ekonomi, sosial, budaya, bisnis,
kelucuan, hingga soal ideologi. Sehingga makna media tidak terlepas dari kebutuhan
dan kepentingan, bahkan kepuasan publik.
Dari media masyarakat melek informasi sekitar hingga yang
terjauh. Dapat membaca apapun dan menangkap apapun yang ditayangkan dan ditulis
di media. Media memiliki peran sentral
dalam tata perubahan masyarakat kita. Melalui media terjadi sirkulasi budaya,
kepentingan, doktrin, hingga ideologi. Dalam arus demokratisasi, media
dimasukkan sebagai salah satu pilar demokrasi karena perannya mengkampanyekan
demokrasi. Media diyakini dapat mengawal demokrasi yang hakiki dalam suatu
komunitas masyarakat.
Ia dapat mengkonsolidasikan massa,
melakukan provokasi, agitasi dan menyatukan orang yang memiliki pandangan sama
tentang suatu hal. Beberapa waktu lalu kita disuguhkan kasus Prita Mulyasari
yang membuat jutaan orang tergerak melawan RS Omni Internasional di Jakarta.
Kasus anak pencuri sandal yang dihukum di Sulawesi membuat gerakan seribu
sandal nasional. Semua itu bermula dari media. Media begitu mudah membesarkan
nama orang, nasib seseorang seakan berada di media. Lihat Ayu Ting-Ting, Zaskia
Gotic, Cita Citata, bahkan Jokowidodo termasuk orang diuntungkan oleh media.
Namun demikian, juga banyak orang dibuli
hidupnya tidak tenang hanya gara-gara ucapannya yang salah atau penampilannya
yang tidak sesuai di media. Masih ingat kasus Viky Presetyo yang membuat kamus
populer Indonesia secara sendiri. Dia kemudian dibuli karena ulahnya yang sok
pinter itu. Dan masih ada beberapa kasus lainnya.
Media
dan Perubahan Sosial
Para pejuang pra-kemerdekaan juga
berjuangan lewat media. Misalnya yang dilakukan Raden Mas Djokomono (Tirtohadisoerjo)
(1880-1918) melalui koran harian Medan
Prijai. Abdul Rivai (1871-1933) mendirikan Bintang Hindia. Wahidin Soediro Husodo membentuk Retnodhoemilah berbahasa Jawa dan Melayu.
HOS Tjokroaminoto mendirikan koran Oetoesan
Hindia. Ahmad Dahlan mendirikan Suara
Muhammadiyah. Dari situ lahir semangat nasionalisme dan patriotisme.
Melalui bacaan-bacaan itu rakyat indonesia menyadari dirinya yang ditindas.
Upaya Soekarno, Hatta, Natsir dan
Sjahrir untuk membakar semangat kebangsaan dan kebebasan tidak bisa dilepaskan
dari kerja-kerja kejurnalistikan. Pada 1926 Soekarno mendirikan kelompok studi Algemene Studieclub serta jurnal Indonesia Muda. Ia menjadi editor
majalah SI, Bendera Islam
(1924-1927). Namun demikian colonial mengintimidasi kebebasan pers ini karena
dianggap membahayakan status quo-nya
Perjuangan di era pasca-kemerdekaan juga
dibarengi penguasaan media. Buku Tanah
Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia mencatat beberapa tokohnya diantaranya:
Nono Anwar Makarim, maktivis angkatan 66, mendirikan Harian Kami. Koran ini menginspirasi lahirnya koran dan majalah
kampus, misalnya Mahasiswa Indonesia
di Kampus UI. Mimbar Demokrasi di ITB, Gelora
Mahasiswa di UGM, dan Gelora
Mahasiswa Indonesia di Malang.Tak lupa Mahbub Junaedi juga mendirikan media
yaitu Duta Masyarakat[1]. Semua
media ini hadir untuk mengontrol kemungkinan kesewenang-wenangan orde lama.
Pada tahun1950an, komunitas pers
mengalami peningkatan peran dengan terbentuknya IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa
Indonesia) yang diketua oleh T Yacob dan SPMI (Serikat Pers Mahasiswa
Indonesia) dikomendani oleh Nugroho Notosusanto. Selanjutnya dua institusi itu
melebur menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) pada 1955. Namun kejayaan
ini tak berumur lama karena demokrasi terpimpin Sukarno berkehendak bahwa semua
AD/ART pers mahasiswa menerapkan satu asas Manipol USDEK[2]. Artinya
pers harus menyuarakan aspirasi partai politik. Kemudian secara perlahan pers
mahasiswa mengalami kemunduran[3].
Selama orde baru tidak ada media yang
bebas dari pantauan rezim Suharto, segala pemberitaan dibatasi pada
program-program pembangunan saja. Wartawan ditampung dalam PWI (Persatuan
Wartawan Indonesia) yang mengeluarkan kode etik versi pemerintah. Penca-butan
surat izin penerbitan akan segera dilakukan jika media berani mengungkap belang
pemerintah. Hingga muncul AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) dibentuk oleh
Gunawan Muham-mad dan kawan-kawan, sebagai tandingan PWI, menolak kebijakan yang
mengkrangkeng war-tawan dan kebebasan pers.
Menjelang Reformasi hadir PPMI[4]
(Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) sebagai wadah kejurnalistikan mahasiswa.
PPMI setidaknya memberi angin segar bagi kebangkitan kejurnalistikan di kalangan
mahasiswa. Cuma, wadah ini tidak mampu dimanfaatkan oleh organisasi gerakan
mahasiswa dengan maksimal. Bahkan antara PPMI dengan organisasi gerakan saling
menempatkan diri sebagai opposisi dan mines
kepercayaan diantara mereka. PPMI lebih dekat pada wilayah akademis dan semata
menulis. Sementara gerakan mahasiswa membungkus diri sebagai aktivis saja.
Padahal diantara keduanya mestinya saling melengkapi dan tidak salig menutup
diri untuk mematerialkan segala gagasan dan apa yang terjadi serta
mempraksiskan segala apa yang diteorikan.
Kekuasaan
dan Juragan Media
Sayangnya setelah reformasi digapai
kebebasan pers dilindungi, malah media digunakan untuk kepentingan pribadi atas
kekuasaan. Media yang ada sekarang telah dikuasai para elit politik. Pemilik
media berlomba-lomba dalam bursa kekuasaan dan sialnya lagi mereka menggunakan
medianya untuk tujuannya itu. Hampir semua media yang ada di Indonesia saat ini
dikuasai oleh politisi. Misalnya, MetroTV
dan Media Indonesia milik Surya
Paloh, ketua umum Partai Nasdem. TVOne
dikuasai Abu Rizal Bakri (ARB), Ketua Umum Golkar versi Bali. ANTV dipegang
oleh Nirwan Bakrie (adik kandung ARB). MNCTV,
SindoTV, GlobalTV, harian Sindo
dipegang Hari Tanoe Sudibyo, pendiri Partai Perindo. Jawa Post milik Dahlan Iskan yang tegas merapat pada Jokowi, begitu
juga Kompas cenderung berpihak pada
KIH (Koalisi Indonesia Hebat).
Berebutnya para juragan media untuk
duduk di kursi kekuasaan membuat berita yang disajikan sering menyudutkan
kalangan tertentu (lawan politik) dan menguntungkan diri sendiri. Kita semua melek pada pilres 2014 lalu, dan bahkan
hingga kini, berita yang ditayangkan TVOne
dan ANTV bertolak belakang dengan MetroTV. TVOne membesar-besarkan Probowo Subianto dan KMP (Koalisi Merah
Putih), sementara MetroTV secara
terus menerus menghadirkan blusukan dan kebaikan Jokowidodo dan KIH.
Sementara media cetak: Jawa Post dan Kompas juga mensupport Jokowi. Pada Juni 2014 lalu, Jawa Post menulis headline dengan judul Si Kaya
(Prabowo) dan Si Miskin (Jokowi).
Disitu Jokowi dicitrakan sebagai sosok kejutan yang membawa harapan besar bagi
perubahan bangsa Indonesia. Seolah-olah hidupnya yang miskin dulu adalah
jaminan bagi keadilan di negara ini. Dan sebaliknya Probowo dicitrakan orang
yang sudah terlena dengan kekayaan dan kemewahan, sehingga kemungkinan jika
Prabowo jadi presiden maka hanya kemewahan yang dilakukan bersama keluarganya.
Pada titik ini media tidak lagi bergerak
pada relnya sebagai kontrol sosial. Pers tak lagi moderat untuk menyampaikan
berita yang benar tentang suatu perkara. Pers tak lagi menjadi tiang demokrasi,
justru sebaliknya menggrogoti demokrasi. Jika benar para pemilik media tersebut
punya kehendak yang kuat untuk meraih kekuasaan di pemilu yang akan datang,
maka selama lima tahun kedepan kita bersiap menerima berita-berita bohong dari
media.
Politik
Redaksi
Coba ingat-ingat, saat Jokowi dinyatakan
menang dalam pemilu 2014 dan dilantik dengan pesta rakyat yang meriah di depan
istana negara dan kawasan Monas. MetroTV
sepanjang hari memberitakan sukacita rakyat, dan keriangan rakyat sembari
menikmati hidangan. Jokowi keluar menyalami rakyat dan dicium tangannya. Tetapi
event yang sama, TVOne justru menayangkan anak kecil yang kehilangan ibunya karena
sibuk pesta. Mengangkat rakyat yang kecopetan di Monas, kemacetan yang
diakibatkan pesta, serta desas-desus rakyat yang memang sengaja diundang dengan
bayaran oleh Jokowi.
Pertanyaannya, mengapa pada kejadian
sama tetapi sense-nya bagi pemirsa
berbeda? Disitulah politik redaksi bergerilya. Politik redaksi adalah kehendak
jajaran redaksi dalam menetukan berita berdasarkan pertimbangan politis.
Redaksi memiliki kuasa penuh untuk mengambil sudut pandang (angle) yang berbeda tentang satu kasus
yang sama dalam berita yang dirilis. Redaksi bebas menentukan mau diarahkan
kemana opini publik: membenci Jokowi atau Prabowo. Disini redaksi bisa
sewenang-sewenang menantukan berita.
Saat saya menjadi wartawan Jawa Post Radar Malang beberapa waktu
lalu. Saya merasakan betul bagaimana politik redaksi dijalankan oleh media.
Penulis (wartawan) dan redaksi punya hak penuh untuk memilih berita yang mana
dan angle apa yang akan diberitakan.
Rumusannya sederhana, media selalu memilih yang menguntungkan secara ekonomi
dan politik. Sehingga kedekatan politik antara objek berita dan yang memilih
berita (redaksi) sangat penting. Faktor ini yang memutuskan suatu berita layak
tayang. Suatu contoh, mengapa saat kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kampus
UIN Maliki terus “dikompori” oleh Radar
Malang.
Sementara dugaan korupsi Universitas
Kanjuruhan Malang (Unikama) dan Universitas Negeri Malang (UNM) yang tidak
kalah besarnya tidak dikorek lagi. Rupa-rupanya, UM dan Unikama lebih rajin
mengiklankan diri di Radar Malang.
Ini contoh kecil saja, masih banyak contoh besar lainnya yang jauh lebih
dahsyat dari itu.
Persma
Harus Bangkit
Pers mahasiswa (Persma) bukanlah sama
dengan pers umum yang meng-cover berita-berita
bersifat informative semata. Persma diharapkan mampu mengkaji permasalahan
sosial yang diberitakan dengan analisis keilmuan secara kritis serta obyektif.
Persma, idealnya, harus berani memberitakan fakta yang benar dan jujur kepada
masyarakat dengan tidak meninggalkan kandungan nilai-nilai humanitas yang harus
tetap dipegangnya.
Menurut Arismunandar, setidaknya ada lima
peran penting Persma dalam mengawal perubahan di tengah kondisi bangsa yang
dikepung oleh para aristokrat-oligarkis ini. Pertama pemasok informasi, Persma mendokumentasikan informasi,
berita, gambar yang dibutuhkan mahasiswa untuk melakukan pengkajian. Kedua, peran motivator, Persma merangsang
aspirasi mahasiswa dan mendorong pada pengembangan aktivitas komunal demi
tujuan gerakan. Ketiga, peran
sosialisasi, Persma menyediakan basis pengetahuan bersama yang dapat
menumbuhkan kohesi dan kesadaran sosial, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk
terlibat dalam gerakan.
Keempat, peran
integrasi, Persma menyediakan seperangkat informasi yang dibutuhkan oleh
mahasiswa untuk saling mengenal satu sama lain, saling bertukar apresiasi serta
sudut pandang analisis yang berbeda dari organisasi lain. Kelima, peran edukator, Persma menyam-paikan berbagai ilmu pengetahuan
dan perkembangannya, serta pasang surut intelektualitas baik di masyarakat
maupun di wilayah akademik[5]. Dengan
begitu akan muncul suatu gerakan perlawanan yang kokoh dan solid. Kekuatan pena
akan mendobrak kejumudan berfikir kaum muda dalam melihat realitas yang semakin
palsu dan penuh lipstik.
Maksimalkan
Dunia Cyber
Cicero, filsuf Italia, menyatakan bahwa
tak ada satu hal pun yang tidak dapat diciptakan atau dihancurkan atau
diperbaiki dengan kata-kata (media). Untuk itu menguasai media adalah suatu
keharusan jika kita masih berniat untuk berdakwah dan menginginkan perubahan
dan kontrol sosial terus jalan. Para agen intelektual saatnya membuat media
tandingan yang berpihak terhadap kepentingan rakyat dan bukan penguasa.
Berkembangnya dunia Cyber sebenarnya mempermudah para agen gerakan untuk memulai
membuat media tandingan. Kita tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak untuk
mendirikan suatu media. Cukup dengan membuat blog atau website.
Masyarakat Indonesia sudah lebih 50 persen kelas menengah dan melek teknologi, ditambah Indonesia
sebagai pengguna sosial media terbesar ke lima di dunia setelah Inggris,
Jepang, dan Brazil. Advokasi dan agitasi akan lebih mudah dilakukan melalui
media cyber yang dapat dengan mudah
dibaca lewat smatrphone mereka. Atas
alasan itu pula filsafatmazhabkepanjen.blogspot.com
ini didirikan. Sayangnya sejauh ini tak banyak organisasi gerakan
memanfaatkan peluang ini dengan baik.
Generasi kita justru disibukkan dengan
soal citra diri masing-masing melalui sosial media (sosmed). Gatged bagus yang dimiliki tidak
dimanfaatkan secara maksimal untuk sesuatu yang penting bagi perubahan tata
kemasyarakatan bumi pertiwi ini. Kita masih tergila-gila dengan update status yang isinya narsis belaka.
Menurut hasil survey, sebagian besar isi pengguna Twitter dan Facebook
berisi soal kegalauan (cinta-cintaan), orang marah-marah, ceramah, bisnis, dan
info tak berbobot lainnya. Ini menunjukkan penggunaan sosmed masih dihantui
untuk kepuasan diri individu. Padahal kita tahu bagaimana sosmed dapat
melahirkan gerakan massal untuk melawan, misalanya kasus Prita Mulyasari dan AL
sebagaimana disebut diawal.
Untuk membuat media Cyber tandingan perlu dikemas dengan baik termasuk teknik
pewartaannya (penulisan dan visualnya) maupun strategi distribusi informasi.
Jika agen-agen gerakan perubahan mampu menguasai dunia Cyber besar kemungkinan control social akan tetap terjaga.
Ajaran-ajaran kebenaran dapat tersalurkan, dan tak kalah pentingnya adalah edukasi
masyarakat juga terbuka.
#filsafatmazhabkepanjen.blogspot.com
[1] Taufik Rahzen et al. Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers
Indonesia. Jakarta: IBoekoe. 2007., hal 266
[2]
Manifesto Politik UUD 1945,
Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian
Indonesia
[5] Satrio Arismunandar. Bergerak!: Peran Pers Mahasiswa dalam Penumbangan Rezim Suharto. Yogyakarta: Genta Press. 2005, hal 28-29.











0 Komentar